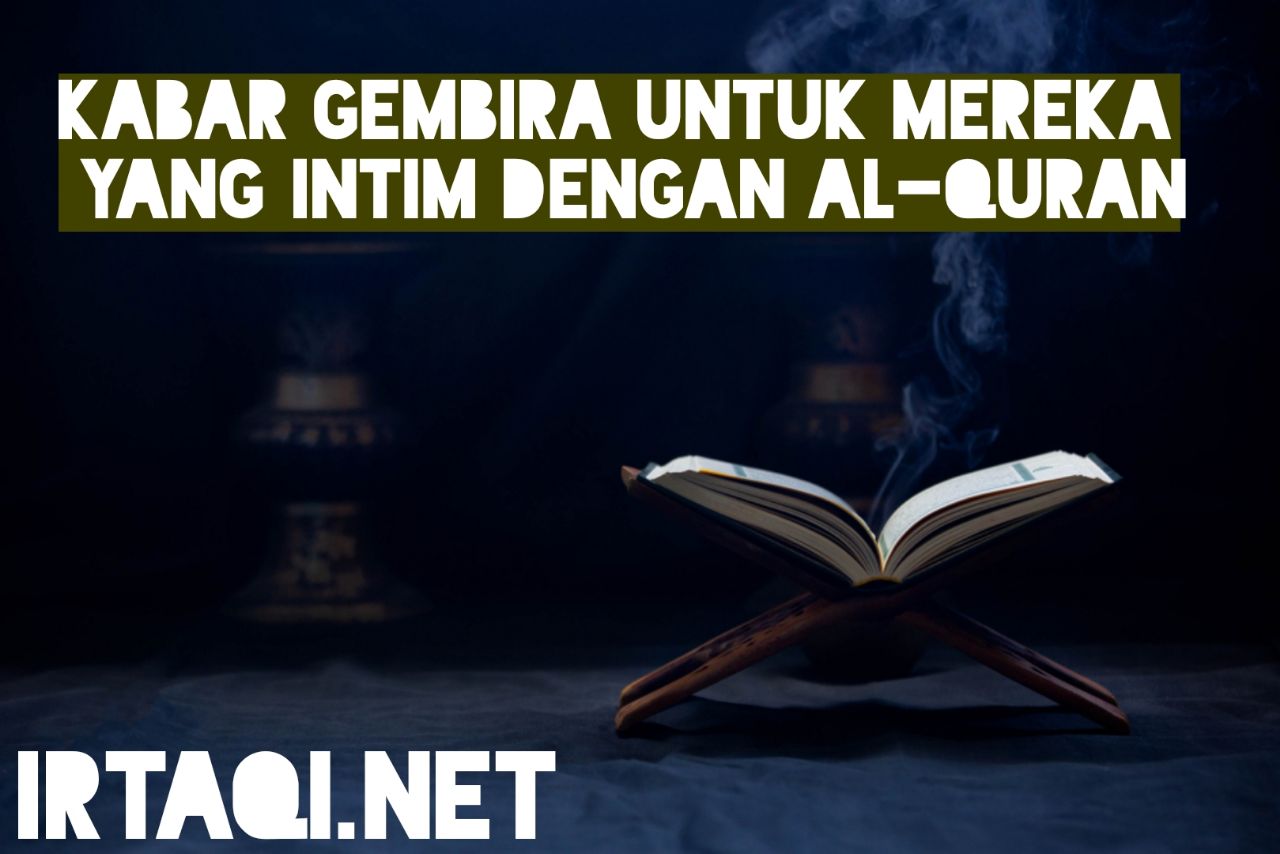Oleh : Ustaz Muafa (Mokhamad Rohma Rozikin/M.R.Rozikin)
Di antara cara cepat mendekat kepada Allah adalah intim dengan Al-Qur’an.
Akrab dengan Al-Qur’an ini mencakup aktifitas menghafal, membaca, memahami maknanya, mengamalkan dan mengajarkan.
Dikisahkan, Imam Ahmad pernah bermimpi melihat Allah, kemudian beliau bertanya,
“Wahai Tuhanku, cara apa yang terbaik untuk mendekat kepadaMu?” jawaban yang beliau terima, “Dengan KalamKu wahai Ahmad”. Beliau bertanya lagi, “Wahai Tuhanku, apakah harus paham atau tidak harus paham?” , dijawab, “Dengan paham maupun tidak paham”.
Kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Majālis Al-‘Asyarah karya Al-Khallāl sebagai berikut,
Artinya,
“Aku (Ahmad bin Hanbal) melihat Tuhan yang memiliki kemuliaan azza wa jalla dalam mimpi. Aku bertanya, ‘Wahai Tuhanku, amalan apa yang paling baik dilakukan oleh orang yang ingin mendekat kepadamu?’ Dia menjawab, ‘Kalamku wahai Ahmad’ Aku bertanya lagi, ‘Wahai Tuhanku, dengan paham ataukah tanpa paham?’ Dia menjawab, ‘Dengan paham atau tidak paham”
***
Kisah di atas juga disebutkan Al-Qusyairī dalam Al-Risālah Al-Qusyairiyyah, Ibnu Al-Jauzī dalam Manāqib Al-Imām Aḥmad, Al-Gazzālī dalam Iḥyā’ ‘Ulūmiddīn, Al-Maqdisī dalam Mukhtaṣar Minhāj Al-Qāṣidīn, Al-Nawawī dalam Al-Tibyān fī ādābi Ḥamalati Al-Qur’an, Al-Żahabī dalam Siyar A‘lām Al-Nubālā’, Ibnu Al-Jazarī dalam Al-Nasyr fī Al-Qirā’āt Al-‘Asyr, dan yang lainnya.
Sebagian orang berpendapat kisah ini dusta dan tidak boleh dinisbahkan kepada imam Ahmad. Ini penilaian yang berlebihan.
Satu-satunya keberatan terhadap kisah ini adalah karena di dalam sanadnya ada perawi yang dianggap bermasalah, yakni Ibnu Miqsam.
Kekeliruan metodologis dalam analisisnya adalah karena menilai Ibnu Miqsam dengan standar dan kriteria jarh dan ta‘dil untuk hadis.
Ini kurang tepat. Sebab, keketatan dalam hadis memang berbeda dengan keketatan dalam riwayat selain hadis. Jangankan hadis, sirah nabi saja diterima dengan longgar. Sebab, jika seluruh perawinya disaring dengan kriteria hadis, maka akan banyak yang tidak lolos karena mayoritas riwayat sirah itu mu‘ḍal, munqaṭi’ dan berisi perawi mubham. Jika Anda pernah mengkaji Sirāh Ibnu Hisyām yang menjadi sumber utama penulisan sirah Nabi ﷺ sampai hari ini, maka Anda akan sering mendapati ungkapan berbunyi “haddaṣanī man lā attahimu” (saya diberitahu orang yang tidak saya tuduh-dusta-), yang menunjukkan perawinya mubham. Jika keketatan menyeleksi riwayat hadis dibawa ke sīrah, maka umat Islam tidak akan pernah bisa menyusun sirah nabinya.
Penerimaan riwayat sīrah memang lebih longgar karena tujuannya bukan untuk menggali hukum halal haram, tetapi untuk ibrah dan mengambil pelajaran. Oleh karena itu, popularitas dan kemasyhuran kisah sudah cukup untuk menerima riwayat sirah yang sanadnya tidak terlalu kuat.
Apalagi riwayat selain Nabi ﷺ . Para ulama tentu saja akan lebih longgar, dan biasanya akan mengketati aspek kritik matannya. Artinya, jika ada riwayat yang matannya bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunah, maka riwayat tersebut ditolak. Tetapi jika tidak, maka diterima.
Masalah melihat Allah dalam mimpi, bukan Imam Ahmad saja yang mengalaminya, tetapi juga diriwayatkan dari sejumlah ulama lainnya dengan sanad sahih. Di antaranya adalah mimpi Raqabah. Ibnu Al-Ja‘d meriwayatkan,
عَنْ رَقَبَةَ قَالَ: ” رَأَيْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي لَأُكْرِمَنَّ مَثْوَاهُ. يَعْنِي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ “( مسند ابن الجعد (ص: 198)
Raqabah bin Maṣqalah adalah pakar hadis besar yang sudah tidak diragukan lagi keṣiqahannya.
Termasuk mimpi Syuraiḥ bin Yunus,
Termasuk mimpi Al-Auza‘ī,
Al-Nawawī (mengutip Al-Qāḍī ‘Iyāḍ) mengatakan bahwa melihat Allah dalam mimpi adalah perkara yang mungkin dan sudah disepakati para ulama (Muafa; sebab melihat dengan mata memang berbeda dengan melihat dalam mimpi). Al-Nawawī berkata,
Artinya,
“Para ulama sepakat mungkin dan benarnya melihat Allah ta’ala dalam mimpi”
Ibnu Taimiyyah juga membenarkan mimpi seorang mukmin melihat Allah. Beliau berkata,
Oleh karena itulah, meskipun Ibnu Miqsam bukan perawi kuat dalam hadis, tetapi beliau adalah orang saleh yang tidak menghalalkan dusta. Al-Khaṭīb Al-Bagdādī dalam kitabnya melukiskan Ibnu Miqsam sebagai berikut,
Artinya,
“beliau adalah seorang lelaki yang saleh”
Dalam hadis, status beliau adalah layyinul hadīṣ, bukan pemalsu hadis. Makna layyinul hadis adalah hadisnya bisa dicatat sebagai i‘tibār. Al-Dāraquṭni malah menegaskan istilah itu tidak membuat orang gugur dari keadilan. Al-Nawawī berkata,
فإذا قاولوا لين الحديث كتب حديثه ونظر اعتباراً، وقال الدارقطني: إذا قلت لين لم يكن ساقطاً، ولكن مجروحاً بشيء لا يسقط عن العدالة (التقريب والتيسير للنووي (ص: 53)
Nah, oleh karena secara matan tidak bermasalah, dan perawi yang dipermasalahkan juga tidak “separah” yang dibayangkan, tidak heran pakar hadis sehebat Al-Żahabī dalam Siyaru A‘lāmi Al-Nubalā’ menyebutkan riwayat Ahmad itu tanpa kritikan apapun. Padahal Al-Żahabī dikenal sensitif dengan riwayat yang bermasalah. Jika Anda akrab dengan kitab ini, maka Anda akan sering mandapati Al-Żahabī mengkritik riwayat-riwayat tentang tokoh yang bermasalah, aneh, bertentangan dengan akal dan sebagainya.
Al-Nawawī juga mengutip kisah tersebut dalam kitab Al-Tibyān tanpa kritikan, padahal Al-Nawawī adalah ahli hadis yang bahkan tidak segan-segan mengkritik dalil mazhab Al-Syāfi‘ī jika memang diketahui beliau tidak bisa dijadikan sebagai dalil.
Jadi, menganggap kisah tersebut dusta adalah berlebihan. Lebih bagus adalah sikap tawaqquf, jika memang belum sempat mengkaji lebih dalam seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Baẓ dan Ibnu Al-‘Uṡaimīn.
Kesimpulannya, kisah Imam Ahmad bermimpi melihat Allah bisa diterima dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an maupun hadis. Wallahua’lam
***
10 Jumādā Al-Ūlā 1442 H