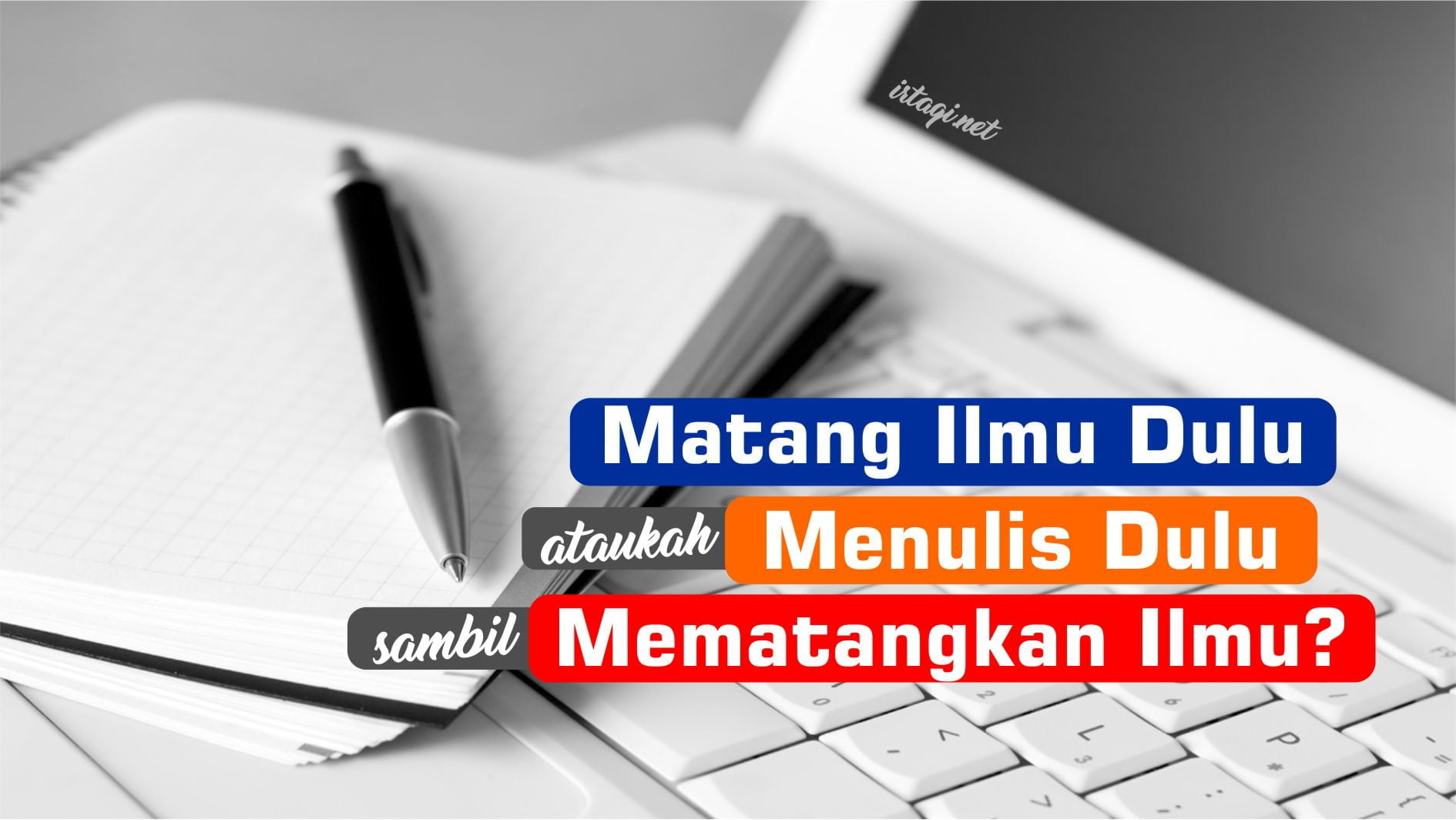Oleh: Ustaz Muafa (Mokhamad Rohma Rozikin/M.R.Rozikin)
Dua-duanya baik dan dua-duanya bisa dipraktekkan. Keduanya adalah cara belajar yang dipraktekkan para ulama di masa lalu sehingga siapa pun bisa memilih salah satu di antara dua cara itu sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing.
Ar-Rofi’i dan Ibnu Ar-Rif’ah adalah contoh ulama Asy-Syafi’iyyah yang memilih untuk mematangkan ilmu terlebih dahulu, menghafalnya dan menguasainya. Setelah merasa matang barulah mulai menulis buku. Cara ini harus diakui adalah cara terberat. Perlu kecerdasan sangat tinggi, hafalan yang kuat dan kesungguhan yang tidak main-main. Umumnya ulama di masa lalu menempuh jalan ini sebelum menulis sebuah buku.
Adapun menulis sambil mematangkan ilmu, maka ini adalah cara belajarnya An-Nawawi. Semua hasil belajar dicatat dengan rapi, disistematisasikan, diurutkan dan ditata dengan runtut lalu dijadikan buku, kemudian dari hasil karya buku itu semua informasi dan pengetahuan yang ada di dalamnya dijadikan bahan untuk mereview, memuroja’ahi dan menghafalkan apa-apa yang perlu untuk dihafalkan. Cara ini lebih ringan, tetapi juga perlu ketelatenan, konsistensi dan ketangguhan tinggi untuk bisa melakukannya. Kelebihan cara ini, semua ide-ide brilian akan tercatat dengan rapi, tingkat kedetailannya bagus, produktivitas melonjak tinggi, dan manfaatnya bisa jauh lebih banyak karena produksi yang dihasilkan juga banyak.
Al-Isnawi berkata,
“Tatkala beliau (An-Nawawi) telah berkompeten untuk meneliti dan menyimpulkan (ilmu), maka beliau berpendapat untuk bersegera melakukan banyak kebaikan dengan cara menjadikan hasil belajar dan apa yang beliau pahami sebagai sebuah karangan yang bisa dimanfaatkan orang yang mengkajinya. Jadi, beliau menjadikan karangannya sebagai hasil belajar (academic achievement) dan menjadikan hasil belajarnya sebagai karangan. Siapa pun yang seperti ini kondisinya, biasanya tidak menghafal selain perkara populer kecuali topik yang tengah ia dalami. Hanya saja, ini adalah tujuan yang sahih dan niat yang indah. Jika bukan karena itu, tidak mungkin beliau (An-Nawawi) bisa mengarang karya sebanyak itu. Beliau (An-Nawawi) rahimahullah memasuki kota Damaskus untuk mencari ilmu dalam usia 18 tahun dan wafat dalam keadaan belum genap 46 tahun sebagaimana akan Anda ketahui dalam biografinya sebentar lagi insya Allah (usia sependek ini dengan produktivitas sederas itu hanya mungkin terjadi jika cara belajarnya adalah belajar sambil menulis). Adapun Ar-Rofi’i, maka beliau menempuh metode pada umumnya. Oleh karena itu, beliau banyak menghafal dan umumnya menghafal topik ilmu yang sudah dibahas (generasi) sebelumnya dan apa yang baru dibahas. Seperti ini pula kondisi Ibnu Ar-Rif’ah radhiyallahu lanhum ajma’in wanafa’ana bihim” (Al-Muhimmad fi Syarhi Ar-Roudhoh wa Ar-Rofi’i, juz 1 hlm 99-100).
Hanya saja, untuk bisa menulis dengan tulisan yang bermutu terkait ilmu-ilmu Islam, tetap saja ada standar minimal yang diperlukan supaya tulisannya berbobot, ilmiah, memiliki landasan yang kokoh dan enak dicerna. Kompetensi minimal ini kalau dalam bahasa Al-Isnawi adalah kompetensi yang membuat seseorang sanggup melakukan “nazhor” (meneliti) dan “tahshil” (menyimpulkan bahasan ilmu).
Saya belum menemukan syarah khusus yang memerinci seperti apa gambaran kemampuan seperti yang diisyarakan Al-Isnawi di atas. Hanya saja, dengan jurus “meraba-raba” melalui pengamatan sejarah belajar sejumlah ulama, saya membayangkan, barangkali orang bisa mencapai kemampuan minimal seperti itu jika dia memiliki kemampuan bahasa Arab yang membuatnya sanggup memahami ilmu-ilmu yang disampaikan dengan bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan tanpa kesulitan sama sekali. Dia tidak harus punya kemampuan bahasa Arab secanggih Sibawaih atau Ibnu Hisyam atau Ibnu Malik. Tetapi dia memiliki bahasa Arab yang cukup untuk menjaring semua macam ilmu yang disampaikan dalam bahasa Arab lewat media apa pun. Selain itu, dia harus mengerti dasar-dasar ilmu Islam yang bersifat epistemologis seperti ulumul qur’an, mushtholah hadis, ushul fikih dan semisalnya. Dia juga perlu tahu ilmu pemetaan kitab agar mengenal nama-nama kitab, pengarangnya, masa disusunnya, ketegorinya, urgensinya dan semisalnya. Dia juga perlu tahu sebagian besar cabang-cabang ilmu Islam, meskipun secara umum tanpa harus menguasai sampai sedetail-detailnya. Tentu saja “rabaan” ini sifatnya terbuka untuk didiskusikan dan insya Allah semakin asyik jika diperdalam dan dipertajam.
Jika kompetensinya di bawah itu, maka kemungkian tulisan yang lahir adalah tulisan-tulisan yang masih rawan dari sisi tanggung jawab ilmiah (kecuali dikoreksikan), hanya mungkin dinikmati kalangan terbatas, dan sulit untuk “hidup terus” sepanjang masa.
اللهم اجعلنا من الذاكرين بانخراطنا في صفوف المتعلمين